Selama satu dekade terakhir saya mempelajari secara aktif dan pasif siklus recruit-develop-deploy-retain di dalam perusahaan maupun studi literatur. Beragam konsep dan praktik pengembangan sumber daya manusia silih berganti, silang sengkarut serta tumpang menindih memenuhi benak dan otak. Satu hal yang selalu saya temui, bahwa siklus pengembangan sumber daya manusia selalu berhenti ketika seorang talent menyodorkan surat cinta (pengunduran diri) kepada manajemen.
Manajemen seakan tergagap menghadapi keputusanh itu. Bangunan sistem talent management dan konstalasi career path seakan runtuh dalam waktu bersamaan. Dalam kondisi panik ini, tawaran tidak realistis mewujud dalam program retaining yang mungkin justru telah diantisipasi sang talent, sehingga apapun tawarannya, keputusan tidak berubah. Palu telah diketuk. Hilang sudah satu investasi penting organisasi dan menyisakan luka mendalam.
Pada kenyataannya tidak setragis itu. Memang benar suatu tragedi kala karyawan star hengkang dari perusahaan. Tetapi sungguh kita tengah menangisi duka yang salah. Hengkangnya seorang talent dari organisasi tidak lebih sebuah bagian dari tour of duty dalam lingkup pengembangan dirinya.
Ya, tapi kan pengembangan dirinya sudah bukan urusan kita lagi.
Bagi talent manager kebanyakan, pandangan ini mungkin benar. Tetapi tidak bagi talent manager yang punya sense of millenial. Perspektif yang futuristik menolak bahwa proses pengembangan sumber daya manusia hanya terjadi di dalam satu organisasi atau satu lingkungan. Berikut adalah bukti-bukti yang akan saya sodorkan untuk memperkuat perspektif ini:
- Generasi Baru Tenaga Kerja
Saya tidak akan memberi label apapun terhadap tenaga kerja yang baru muncul di era media sosial. Yang pasti kita ketahui bersama generasi baru ini muncul ke ranah dunia industri tidak dengan kepala kosong. Mereka sudah memiliki skill dan knowledge yang mungkin oleh generasi sebelumnya didapat melalui pengabdian bertahun-tahun. Kemampuan teamwork yang alami, pola komunikasi efektif, metode pengambilan keputusan dan tentu saja computer-internet savvy merupakan beberapa skill yang telah lengkap mengisi portofolio mereka.
Kemampuan alami ini kadang membuat iri para pendahulunya sehingga membuat genarasi sebelumnya gerah dan mencari-cari apa yang mereka miliki dan tidak dimiliki generasi baru tenaga kerja. Salah duanya adalah ketahanan kerja dan loyalitas. Lebih jauh lagi beragam prejudice dan label disasarkan kepada para generasi baru ini. Kita tidak sedang akan membahas ini (mungkin nanti).
Seiring dengan prejudice tersebut, pada kenyataannya generasi baru melihat lowongan pekerjaan sebagai etalase produk yang dapat dipilih dan dipilah sekehendak hati. Jika satu produk sudah dibeli maka masih banyak produk lain yang mengantri untuk dikonsumsi. Tinggal dilihat berapa banyak modal yang dimiliki untuk membelinya. JIka sudah begini, maka definisi tentang mendaki karir berubah. Karir bukan milik perusahaan dan tidak ditentukan oleh satu organisasi. Karir adalah peta perjalanan yang dilukiskan sendiri oleh pemilik karir.
- Anekdot yang Menjadi Nyata
Pernahkah membaca sebuah anekdot berupa percakapan antara CFO dan CEO tentang employee training? JIka belum, inilah kilasannya:
CFO : “What if we train employees and then they leave?”
CEO : “What if we don’t and they stay?”
Inilah realitasnya kawan. Brutal but true. Organisasi sering ditinggal oleh karyawan bintangnya dan menyisakan karyawan “X-rated”. Gambaran anekdot tersebut tidak terbatas pada training karyawan. Segala hal yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia masuk dalam radar. Mulai dari Coaching & Counseling sampai pada Project Assignment, semua tidak terhindar dari serangan ini. Bahwa naif jika kita masih menganggap karyawan yang telah dikembangkan sedemikian rupa memiliki atensi untuk membalas segala “kebaikan” kita dengan terus bekerja di tempat yang sama.
Pokok persoalannya terkadang meleset dan organisasi perlu memaknai ulang dirinya sebagai orang tua. Bahwa sejatinya seorang anak yang dibesarkan, pada akhirnya dia sendiri yang akan menentukan masa depannya. Tugas orang tua adalah memastikan bahwa anak dilepas dalam kondisi siap bertahan di dunia luar sembari memonitor apakah anak ada keinginan kembali ke rumah dan membantu orang tua. Pintu rumah selalu terbuka.
Adalah sebuah tugas mulia bagi seorang talent manager untuk mengedukasi para user bahwa bukan loyalitas yang membuat organisasi bertumbuh-kembang. Sejatinya, loyalitas hanya tumbuh subur di kalangan karyawan generasi pertama (sejauh yang saya tahu) dan gagal diturunkan pada generasi setelahnya. Apa sebab kalau bukan lagi-lagi prejudice terhadap generasi baru yang “tidak tahu tata krama” bekerja.
Menjadi absurd jika kita mengamini bukan loyalitas yang menggerakkan organisasi tapi tetap memaksa setiap orang menghabiskan seluruh karirnya di satu tempat. Dan kita tidak sedang membicarakan apa yang membuat karyawan akan stay lama di suatu perusahaan. Jadi, kuburkanlah harapan itu.
- Selalu Ada Pilihan “Buy”
Human asset value adalah grafik keramat yang sering dijadikan jimat bagi para talent manager. Keberadaannya menjadi peneduh dalam debat pada forum people review, sekaligus menjadi pemancing kerusuhan saat manajemen mulai mengisi Replacement Table Chart (RTC). Pasalnya, kita tidak selalu yakin pada data yang dipaparkan. Se-valid apapun data itu.
Kenyataannya selalu ada pilihan “Buy” di samping “Build”. RTC adalah saksinya. Pilihan itu selalu membayang sekalipun seorang talent manager kelas wahid mengatakan data yang ia miliki dapat dipercaya 150%. Bukan masalah validitas yang dipertentangkan. Masalah ini sesederhana pilihan makan di restoran, mau dine in atau take away. Selalu ada pilihan akan ada pihak lain yang membereskan segala sesuatunya untuk kita. Tinggal seberapa jauh dan lama kita sanggup mengelolanya.
Kenapa begitu, karena pilihan tersebut beririsan dengan kebutuhan perusahaan. Membeli talent, berarti menyerahkan kepada pihak lain metode pengembangan kompetensi serta pembentukan value talent tersebut. Kompetensi mudah diseleksi, tetapi tidak dengan value. Membentuk value bukan pekerjaan mudah, tetapi jauh lebih mudah daripada menyandingkan value yang telah terbentuk dengan value baru. Para pembeli talent pasti sadar dengan konsekuensi ini.
Terlepas dari konsekuensi negatif yang diterima, buying talent adalah aktivitas umum yang dilakukan setiap organisasi untuk mengisi kekosongan posisi. Artinya, jika demand bertabuh maka supply menggelegak, dan inilah yang dilakukan para talent. Sekedar memenuhi demand yang muncul di pasar talent. Tidak percaya? Cek saja berapa akun aplikasi pencari kerja yang dimiliki karyawan anda.
Sebelum kita jauh menekuri situasi simalakama ini, mending kita mulai membiasakan diri kita dan menguatkan hati, karena seburuk-buruknya mantan adalah mereka yang gagal move-on. Dan sebaik-baiknya jomblo adalah mereka yang memiliki banyak teman.
Paragraf di atas bukan sekedar luapan jiwa alay yang tak tersalurkan. Dalam menjawab pertanyaan artikel ini, biarkan saya menegaskan bahwa mindset talent management di masa sebelum digital sulit diterapkan saat ini. Domain talent management sudah bukan lagi intra-organisasi. Talent management menjadi inisiatif yang lintas organisasi bahkan lintas ekosistem.
Keluasan lingkup talent management dapat disandingkan dengan marketing management. Beberapa aplikasi pencari kerja sebenarnya sudah memulai hal ini tanpa disadari. Dengan membuka data portofolio seorang pencari kerja kepada khalayak, sejatinya sudah cukup bagi seorang talent manager mengumpulkan data talent untuk mengisi talent pool-nya.
Jadi, talent management masih relevan saudara-saudara. Hanya mindset-nya saja yang wajib diubah. Prediksi saya tak lama lagi peran talent manager akan digantikan oleh para start-upers berbekal sedikit pengetahuan tentang talent mapping. Satu lagi profesi berakhir di tangan teknologi.

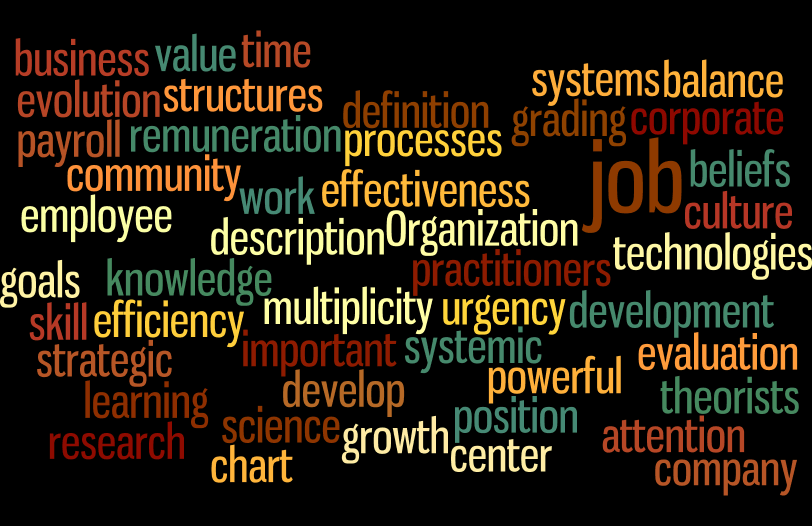
Leave a comment